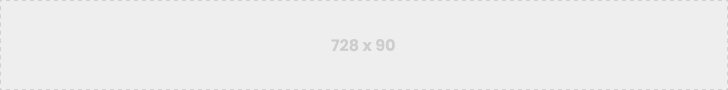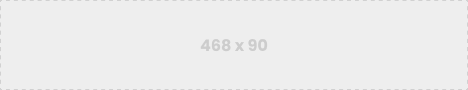Sula: Ruangan Rindu yang Gelap

Oleh: Mohtar Umasugi
Beta memulai tulisan ini bukan dari data statistik atau laporan pembangunan. Tapi dari rindu. Rindu akan tanah yang dulu disebut mutiara di bibir Pasifik. Sebuah kabupaten yang lahir dari sejarah panjang perjuangan dan semangat pemekaran. Tapi kini, saat Beta kembali menapakkan kaki di negeri ini, Beta merasa seolah-olah masuk ke sebuah ruangan—ruangan rindu—yang gelap dan tak bercahaya.
Ada banyak hal yang membuat Beta merasa seperti itu. Jalanan yang rusak, pasar yang sepi, pelabuhan yang mati suri, dan sekolah yang kekurangan guru. Tapi yang paling terasa, adalah ketiadaan harapan. Orang-orang bicara tentang perubahan, tapi perubahan itu terasa jauh seperti ombak yang memecah di tengah laut—keras tapi tak sampai ke pantai.
Sula hari ini bukan kekurangan potensi, tapi kekurangan arah. Pemerintahan seakan terjebak dalam pusaran formalitas tanpa keberanian melompat lebih jauh untuk berpikir visioner. Anggaran belanja daerah seakan menjadi rutinitas tahunan yang sekadar mengulangi pola, tanpa keberpihakan kuat terhadap pembangunan sektor riil masyarakat.
Di sektor pendidikan, kita masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur sekolah. Di sektor kesehatan, masyarakat di pulau-pulau terluar harus bertaruh nyawa untuk bisa mendapat layanan medis dasar. Lalu sektor ekonomi? Kita belum benar-benar membangun industrialisasi lokal yang berbasis potensi wilayah: perikanan, pertanian, dan pariwisata bahari masih sebatas wacana.
Yang membuat ruang rindu ini makin gelap adalah hilangnya semangat kolektif sebagai sebuah komunitas budaya. Di tengah gempuran modernisasi, Sula kehilangan ritme khasnya. Kearifan lokal perlahan memudar, tergantikan oleh praktik-praktik transaksional dalam politik dan sosial. Kita kehilangan budaya malu, budaya gotong royong, bahkan budaya intelektual yang dulu dibanggakan.
Sula seperti rumah besar yang listriknya padam. Kita tahu di mana letak saklar cahaya, tapi tak ada yang cukup berani menyalakannya. Kita terlalu sibuk berselisih tentang siapa yang harus memegang saklar, hingga lupa bahwa yang kita butuhkan adalah terang, bukan siapa yang menyalakan.
Meski ruang ini gelap, Beta percaya masih ada cahaya. Cahaya itu ada dalam semangat anak muda yang mulai bangkit, dalam doa para orang tua yang tak pernah putus berharap, dan dalam jeritan rakyat kecil yang masih percaya bahwa keadilan bisa hadir. Kita hanya butuh pemimpin yang mampu menyalakan cahaya itu. Bukan pemimpin yang hanya hadir di baliho atau panggung seremoni, tapi pemimpin yang mau menyusuri lorong-lorong gelap rindu ini dan menjadi pelita.
Akhirnya, tulisan ini bukan sekadar kritik. Ini adalah panggilan. Untuk kita semua, agar kembali menyinari Sula dengan cinta, kerja nyata, dan keberanian mengambil langkah besar. Sebab tanah ini bukan sekadar ruang tinggal. Ia adalah ruang rindu yang menanti cahaya—dan kitalah yang harus membawanya.***
Fagudu, 8 April 2025